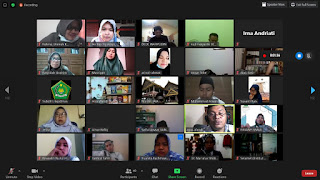Sunday, September 14, 2025
Moderasi Beragama: Jalan Damai atau Alat Kendali?
 Hanya sebuah komunitas kecil yang sedang fokus menikmati hidup sambil mengisi waktu untuk ngeblog.
Hanya sebuah komunitas kecil yang sedang fokus menikmati hidup sambil mengisi waktu untuk ngeblog.
Friday, September 12, 2025
Ketika Agama Membeku: Seruan Mun’im Sirry untuk Berpikir Bebas
Agama sejatinya hadir sebagai cahaya yang membebaskan, bukan belenggu yang membatasi. Namun dalam sejarah panjang peradaban, agama kerap direduksi menjadi sekadar kumpulan doktrin kaku, ritual yang beku, atau simbol-simbol yang kehilangan ruh. Inilah yang dikritisi oleh Mun’im Sirry dalam gagasannya Think Outside The Box—sebuah ajakan berani untuk membebaskan agama dari penjara konservatisme.
Berpikir di luar kotak
berarti membuka ruang refleksi kritis, tanpa harus meruntuhkan fondasi iman.
Konservatisme sering kali memenjarakan agama dalam tafsir tunggal, menutup
kemungkinan dialog dengan zaman, dan mengabaikan kompleksitas realitas sosial. Mun’im
Sirry mengingatkan bahwa agama harus terus hidup, tumbuh, dan berdialog dengan
konteks. Iman yang sehat tidak anti-kritik, justru menguat ketika diuji oleh
pertanyaan-pertanyaan segar.
Pendekatan ini bukan
sekadar upaya intelektual, tetapi gerakan spiritual untuk memurnikan agama dari
belenggu ideologisasi yang sempit. Kita diajak melihat agama bukan hanya
sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai energi transformatif yang mampu
memberi jawaban atas persoalan kemanusiaan modern.
Membebaskan agama dari
penjara konservatisme bukan berarti menolak tradisi, melainkan menyelamatkannya
dari kebekuan. Ini adalah panggilan untuk terus menggali makna, menantang
kemapanan berpikir, dan membiarkan agama kembali pada fungsinya yang hakiki,
menjadi jalan pembebasan, pencerahan, dan rahmat bagi semesta.
Bagaimana menurut Anda, apakah agama di
sekitar kita masih mampu memberi jawaban atas persoalan zaman, atau justru
terjebak dalam formalitas? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, mari
bersama-sama belajar berpikir di luar kotak, agar agama kembali menjadi sumber
inspirasi, bukan sekadar aturan tanpa jiwa.
 Hanya sebuah komunitas kecil yang sedang fokus menikmati hidup sambil mengisi waktu untuk ngeblog.
Hanya sebuah komunitas kecil yang sedang fokus menikmati hidup sambil mengisi waktu untuk ngeblog.
Wednesday, December 9, 2020
Pandangan Aksin Wijaya Terhadap Dominasi Nalar Arab Dalam Teks Keagamaan
Menalar autentisitas wahyu Tuhan, sejatinya bukan untuk mengundang polemik di tengah-tengah masyarakat muslim, namun lebih kepada menampakkan sebuah model kegelisah baru seperti yang dituangkan Aksin Wijaya dalam buku karyanya yang sangat fenomenal. Aksan Wijaya ingin melontarkan gagasan-gagasan yang mempermasalahkan Mushaf Utsmani yang oleh sebagian besar pengkaji Al-Qur'an justru tidak lagi menjadi sebuah masalah. Beberapa pemikir kontemporer, seperti Amin al-Khuli, Fazlur Rahman, Abdul Karim Soroush, Hassan Hanafi, dan beberapa tokoh pemikir lainnya telah menawarkan sekian banyak metodologi serta serangkaian pemikiran kritis lainnya tentang Al-Qur'an, justru tidak menemukan kritikannya terhadap Mushaf Usmani sebagai korpus yang pantas digugat dan dipersoalkan, walaupun sebenarnya mereka bisa saja mempertanyakan proses kodifikasi yang terjadi di masa Usman bin Affan.
Ada satu hal yang menarik untuk dikemukakan pada artikel kali ini adalah terkait perdebatan seputar ke-qadim-an wahyu Tuhan. Istilah tentang qadim mestinya tidak digeneralisasi pada semua sesuatu yang berhubungan dengan wahyu Tuhan, sebab wahyu Tuhan menurut Aksan Wijaya telah mengalami distorsi hebat.
Wahyu Tuhan yang telah dijanjikan terpelihara oleh Tuhan, kini tidak lagi bersama kita, ia berada di haribaan-Nya. Wahyu Tuhan yang kekal dan abadi maksudnya adalah bahwa yang berada di haribaan Tuhan, bukan yang berada di tangan manusia saat ini.
Wahyu Tuhan yang telah dibawa oleh Muhammad Saw. kepada masyarakat Islam pada fase awal di negeri gurun pasir itu yang masih dalam tahap wacana lisan yang disebut dengan Al-Qur'an, kini telah tereduksi dan mengalami penjara di language Arab dan teks mushaf ustmani. Ia telah menjadi teks tulisan, yang sempurna lahir di era khalifah Usman bin Affan. apatah lagi setelah munculnya teknologi percetakan yang dapat mengabadikan wacana lisan ke dalam sebuah teks tulisan. Sebagai teks tulisan, di mana cara memahaminya tidak lagi bergantung pada kehadiran subjek penutur sebagaimana wacana lisan, maka tidak lagi hadir bersama subjek yang membawanyya dan mengucapkannya, melainkan hadir bersama teks tulisan di atas kertas. lalu masihkan Mushaf Ustmani, yang selama ini dirancukan dengan al-Qur'an dan wahyu dikatakan qadim, hadir sejak dahulu kala sebelum kehadiran manusia di muka bumi ini.
Umat Islam meyakini bahwa wahyu Tuhan bersifat suci dan sakral, karena ia bagian dari diri Tuhan, sedangkan yang dimaksud dengan wahyu Tuhan di dunia ini ditujukan pada Mushaf Ustmani. dan tentu pada gilirannya Mushaf Ustmani dianggap dan dinilai suci. Ini jelas sebuah reduksi yang mengagumkan yang tidak terdeteksi secara epistemologis, sehingga tak satupun orang yang tidak percaya bahwa apa yang ada di tangan kita saat ini sebagai sesuatu yang suci, lebih-lebih di sampul luar kitab tersebut terdapat ayat yang mendukung kesuciannya sebagai wahyu Tuhan, sebuah potongan ayat bertuliskan "la yammassahu illal muththahharun" (QS. Al-Waqiah: 79). dan akibatnya semua orang menghormati Mushaf Ustmani sebagaimana layaknya menghormati wahyu Tuhan.
Penyamaan Mushaf Ustmani dengan wahyu Tuhan seperti yang telah disampaikan di atas menjadi sebuah labelisasi suci yang dogmatis. Jika wahyu Tuhan diyakini sebagai yang suci, maka yang suci bukan maknanya, tetapi juga lafazd yang menjadi wadahnya. Oleh karena Mushaf Ustmani diyakin sebagai sebagai perwujudan wahyu Tuhan yang suci, demikian pula unsur-unsur yang berhubungan dengan Mushaf. Bagi seorang yang ingin Mushaf, di persyaratkan harus memiliki wudhu sebagai anda kesucian, baik suci dari hadis kecil maupun hadis besar, maupun suci dari zat dirinya sebagai seorang muslim. Membaca Mushaf, sekalipun tidak mengetahui maknanya, diyakini akan mendapat pahala dari Tuhan, yaitu pahala dari penghargaannya terhadap lafadz mushaf yang suci, sebagaimana membaca al-Qur'an. Karena itu, tradisi bacaan dengan sura merdu semarak di mana-mana, khususnya bagi kalangan awam yang tidak dapat memahami bahasa tulisan.
Keyakinan terhadap lafadz Mushaf Ustmani sebagai sesuatu yang suci pada gilirannya mempengaruhi keyakinan bahwa bahasa Arab yang digunakan oleh Mushaf Ustmani sebagai yang suci. Kesucian bahasa Arab bukan saja terletak pada bahasa Arab Mushaf Ustmani, tetapi juga bahasa Arab masyarakat Arab pada umumnya, baik dalam bentuk bahasa tulisan, puisi, karya ilmiah dan lain sebagainya. Hingga kemudian bahasa Arab dijadikan sebagai pelajaran khusus dalam lembaga pendidikan keagamaan, yang pada akhirnya kian menambah kesakralan bahasa Arab.
Ada satu narasi yang tersirat dibalik karya Aksin Wijaya bahwa jika sekiranya pesan Tuhan dapat lepas dari jeratan itu, maka diperlukan sebuah analisis yang bercorak filosofis-dekonstrukif. kita mencoba mendialogkan pesan Tuhan dengan cara yang bebas, lepas dari bayang-bayang budaya Arab klasik dan selanjutnya kita menggali pesan Tuhan dari mushaf ustmani, dimana pesan Tuhan terpenjara di dalamnya. Dialog bebas penting karena Mushaf Ustmani ini bukan lagi murni wahyu Tuhan sebagaimana yang dijanjikan akan dijaga, melainkan perangkap budaya Arab yang jika kita tidak kritis, tentu kita juga akan terperangkap dalam penjara yang sama. Selamat Membaca dan Salam Literasi
Sumber Bacaan:
Aksin Wijaya, Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan; Kritik Atas Nalar Tafsir Gender, (Cet. I) Yogyakarta: IRCiSoD, 2020 (ISBN 978-623-6699-17-1)
Wednesday, September 23, 2020
Pengantar PRA, RRA dan Pengelolaan Program Kegiatan Bersama Masyarakat
Masyarakat harus senantiasa terus
menerus diajak berpikir dan menganalisis secara kritis keadaan dan masalah
mereka sendiri. Hanya dengan demikian mereka akan mampu memiliki wawasan baru,
kepekaan dan kesadaran memungkinkan mereka memiliki keinginan untuk bertindak,
melakukan sesuatu untuk merubah keadaan yang mereka alami. Tindakan mereka itu
kemudian dinilai, direnungkan kembali, dikaji-ulang untuk memperoleh wawasan
baru lagi, pelajaran berharga yang akan menjaga arah tindakan-tindakan mereka
berikutnya.
Mengorganisir masyarakat adalah
bukan pekerjaan mudah apalagi peneliti pemula, ada banyak hal yang perlu
dipersiapkan serta langkah yang harus dikuasai, seperti bagaimana mempersiapkan
masyarakat sendiri untuk menjadi pelaku utama dalam aksi tersebut dan tanpa
terkesan bahwa mereka digurui. Masyarakat harus senantiasa dilibatkan dalam
setiap hal dari sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
tindak-lanjut suatu aksi. Merekalah yang akan menentukan aksi serta tujuan-tujuan
yang ingin mereka capai.
Lalu peran peneliti luar atau
pengorganisir masyarakat dalam seluruh proses rangkaian aksi tersebut, apa? Tak
lebih adalah hanya sebagai fasilitator
yang membantu masyarakat menemukan cita-cita dan harapannya secara sistematis
termasuk menyediakan informasi penting yang mereka butuhkan dari luar.
Mengorgansir masyarakat, tentunya
memiliki tujuan untuk mencapai perubahan sosial yang lebih baik, lebih besar
dan lebih luas. Namun, masih cukup banyak pengorgansir masyarakat yang sering
kesulitan merumuskan apa yang mereka perjuangkan dalam jangka panjang. Sehingga
menurut Agus Afandi sebagai instruktur dalam kegiatan Shortcourse Pengabdian
Kepada Masyarakat Dirjen Pendidikan Islam Tahun 2020 bahwa pengelolaan program
atau kegiatan bersama masyarakat harus melalui tahapan-tahapan terstruktur,
mulai dari identifikasi masalah, perencanaan atau desain program, pelaksanaan
dan pemantauan. Oleh karena itu harapan beliau kepada peserta pelatihan bahwa
dalam mempersiapkan program kegiatan bersama masyarakat tidak asal-asalan,
melainkan melalui persiapan yang terencana dan matang dalam program tersebut.
Dalam Pelatihan tersebut,
Instruktur banyak memberikan simulasi, dimulai dari temuan problem yang sudah
dirumuskan pada praktek dan simulasi Partisipatory Rural Appraisal (PRA)
Dan Rapid Rural Appraisal (RRA). Pada dasarnya prinsip-prinsip PRA dan
RRA adalah memutar kembali proses belajar masyarakat, memperbaiki
kesalahan-kesalahan, triangulasi, menemukan keragamaan, mengutamakan fasilitas
proses, membangun kesadaran kritis masyarakat dan tanggung jawab serta siap
berbagi bersama dalam mewujudkan transformasi sosial yang lebih baik.
Selain itu, instruktur juga
berbagi tentang bagaimana proses pengorganisasian yang baik, yaitu : mulai dari
rakyat itu sendiri, masyarakat diajak berpikir kritis, melakukan analisis
kearah pemahaman bersama, capai pengetahuan, kesadaran, perilaku baru, lakukan
tindakan atau aksi serta evaluasi tindakan itu.
Proses pengorganisasian
memerlukana tahapan-tahapan seperti berikut: memulai pendekatan, memfasilitasi
proses, merancang strategi, mengerahkan tindakan, menata organisasi, membangun
sistem pendukung.
Dalam keseluruhan proses atau langkah perumusan strategis tersebut, peserta pelatihan tetap jangan lupa bahwa dia harus membuatnya semudah mungkin dipahami oleh masyarakat.
Oleh : Nurdin, S.Fil.I., M.Fil.I (IAI As'adiyah Sengkang)
 Hanya sebuah komunitas kecil yang sedang fokus menikmati hidup sambil mengisi waktu untuk ngeblog.
Hanya sebuah komunitas kecil yang sedang fokus menikmati hidup sambil mengisi waktu untuk ngeblog.
Sunday, September 6, 2020
AKAL, SARANA ATAU SUMBER? MENELAAH PERAN AKAL DALAM PRINSIP BERAGAMA
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sebenarnya sudah ada dalam diri setiap manusia, siapapun orangnya, sebagai manusia tentu harus mengerti dan tahu hakikat kemanusiaannya. Dengan itu kita akan diberikan pilihan berjalan dengan fitrah kemanusiaan kita atau kita akan berjalan berlawanan arah dengan fitrah kemanusiaan.
Berjalan dengan fitrah kemanusiaan sesungguhnya akan mengantarkan kita sampai kepada tujuan kita yang sesungguhnya. Manusia senantiasa mencari sesuatu yang sempurna dalam hidupnya. Pencarian yang sempurna tentu melalui sebuah proses yang panjang dan melelahkan. Pada mulanya manusia mencari yang diinginkan itu pada hal-hal yang bersifat materi atau kebendaan, berupa harta, uang, kecantikan fisik yang pada intinya adalah kemewahan dunia. Untuk hal-hal yang sifatnya materi tentu panca indera merupakan alat utama untuk mendapatkannya. Capaian yang kita raih akan terasa ketidakpuasan karena segala yang bersifat materi-jasmaniah pastilah mengalami perubahan dan akhirnya musnah. Logika mengajarkan kepada kita bahwa yang ditangkap oleh indera seringkali melahirkan tipuan, bahkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Sebuah Fatamorgana yang kita saksikan di siang hari, dari kejauhan kita melihat ada air, namun hakikatnya bukan air yang kita lihat melainkan hanya fatamorgana. Ini adalah sebuah gambaran sederhana bahwa betapa tidak sepatutnya kita percaya terhadap segala sesuatu yang empirik sebagai sebuah kebenaran yang hakiki.
Berangkat dari sini kita butuh sebuah pegangan kuat agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Untuk mencari yang sempurna, tampaknya akal amat perlu dikedepankan. Bagi manusia, akal merupakan penuntun untuk mengetahui kebenaran. Al-qur'an sangat mengapresiasi betapa terpujinya mereka yang mampu menggunakan akalnya dengan baik. Bahkan, mereka yang tidak memfungsikan akalnya dengan baik mereka diberikan predikat binatang bahkan lebih rendah dari binatang.
QS. Al-A'raf : 179
وَلَقَدۡ ذَرَأۡنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ لَهُمۡ قُلُوبٞ لَّا يَفۡقَهُونَ بِهَا وَلَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانٞ لَّا يَسۡمَعُونَ بِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَٰمِ
بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ
Terjemahnya:
Dan
sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan
manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami
(ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya
untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga
(tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah
orang-orang yang lalai.
Penting bagi kita agar memfungsikan akal dengan baik, diasah dan dilatih agar dapat mengenal Sang Pencipta-Nya. Bahkan dalam literatur filsafat Islam mengakui bahwa akal dapat digunakan untuk membuktikan eksistensi atau adanya Tuhan.
Satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan ini adalah kategorisasi akal sebagai daya/sarana dan sebagai sumber. Adakalanya daya akal digunakan untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, serta dianggap sebagai sarana mengenali ajaran-ajaran wahyu. Namun, tak jarang daya akal itu didudukkan di bangku pengadilan dan dipersepsi sebagai sumber khas untuk memproduksi hukum syariat.
Yang umumnya dipandang sebelah mata, bahkan dilecehkan posisinya, adalah akal sebagai sumber; bukan sebagai sarana pengetahuan. Karena, setidaknya dikalangan pemikir Islam, tak seorang pun yang berbeda pendapat tentang urgensi akal dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Kendati menurut sebagian tokoh Kristen, Posisi semacam ini juga disangkal akal. Mereka yakin, demi meraih iman, pemahaman dan pemikiran harus ditepikan.
Mungkin diantara kita ada yang bertanya apakah akal itu? tidak seorang pun mengetahui hakikat akal. Kita tidak dapat mengetahui hakikat mutiara berharga ini. Kita hanya mampu mengetahuinya melalui efek-efek yang ditimbulkan, bisa juga melalui fungsinya. Pada umumnya para filosof mendefinisikan akal berdasarkan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh akal.
Syaikh Syihabuddin Suhrawardi Al-Maqtul menjelaskan bahwa yang pertama diciptakan Allah adalah mutiara cemerlang yang dinamai Akal. Mutiara ini dilekatkan padanya tiga sifat. yaitu : pertama, kemampuan untuk mengenal Allah. Kedua, diberikan kepadanya kemampuan untuk mengenal dirinya, dan Ketiga, Kemampuan untuk mengetahui apa yang belum ada dan kemudian ada. Dan dari kemampuan mengenal Allah muncullah keindahan. Dari kemampuan mengenal dirinya muncullah cinta. Serta kemampuan mengenal apa yang belum ada kemudian ada timbullah kesedihan. Dan dari ketiganya ini adalah bersumber dari satu realitas.
Akal merupakan pelita pemahaman dan penyimpulan. Tanpa bantuan cahayanya, memahami Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sukar, bahkan bisa mustahil. Akal meyakinkan manusia sebuah nuktah, bahwa penciptaan dan keberadaannya tidak sia-sia; dia didatangkan ke dunia dalam rangka menempuh jenjang kesempurnaan mutlak dan meraih keselamatan abadi. Akal juga mampu memahamkan bahwa untuk tujuan itu, manusia harus mengerjakan apapun yang di ridhoi Allah dan menghindari yang dibenci-Nya. Namun, akal akan berhenti lemah sampai batas menyingkap rincian dan seluk-beluk parsial jalan keselamatan itu; batas yang tak sanggup di lampauinya. Hanya dengan arahan wahyu, manusia bisa mengetahui rincian seluk beluk perjalanannya dan cara menempuhnya. Tanpa petunjuk wahyu, akal bukan lagi mitra manusia yang sepatutnya menerangkan aneka hubungan tutur dan prilakunya di dunia ini dengan pengaruh dan dampaknya di akhirat sana.
Lalu peran akal apa? Akal sebagai tolok ukur, akal mengafirmasi kebenaran agama, akal membuktikan prinsip-prinsip keimanan, akal melindungi Agama dari penyimpangan, Akal sebagai kunci dan pelita untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
Sumber Bacaan:
- Hasan Yusufian & Ahmad Husain Sharifi, Akal & Wahyu; Tentang Rasionalitas Dalam Ilmu, Agama dan Filsafat, (Cet.1; Jakarta: Sadra Press, 2011)
- Muh. Ridwan Z. Menemukan Yang Dicari; Sebuah Perdebatan dari Logika hingga Filsafat, TT
- Nurdin, Orisinalitas Akal dan Metafisika Al-Qur'an (Menangkap Makna-Makna Tauhid), Skripsi .
 Hanya sebuah komunitas kecil yang sedang fokus menikmati hidup sambil mengisi waktu untuk ngeblog.
Hanya sebuah komunitas kecil yang sedang fokus menikmati hidup sambil mengisi waktu untuk ngeblog.